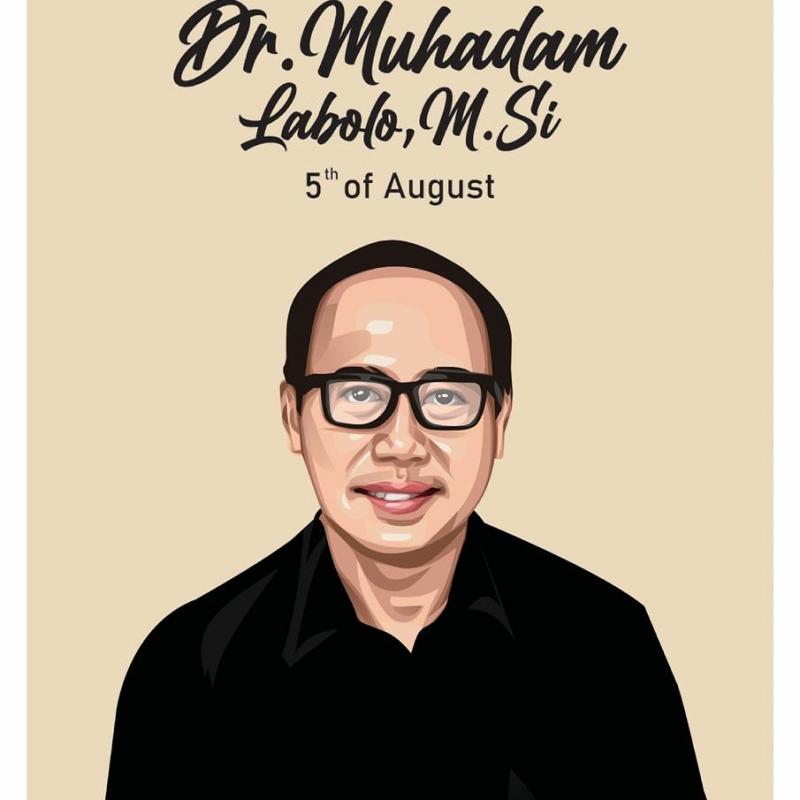
Penulis : Dr Muhadam Labolo (Dosen senior IPDN)
Pemandangan korupsi di sekitar kita rasanya tak mengejutkan lagi. Meminjam istilah mahkamah, serangan korupsi kini semakin masif, terstruktur, sistematis, dan terencana. Masif bergerak di semua lapis kekuasaan dalam relasi idiologis maupun biologis. Terstruktur terjadi di puncak hingga level terbawah. Sistematis di desain agar tampak legal. Terencana di susun sejak pembahasan hingga ketuk palu. Dalam setahun terakhir ada OTT terhadap Bupati Langkat, Penajam Pasir Utara & Bogor.
Realitas ini membuat sebagian kita berada di ambang frustasi. Kesan itu muncul ketika dialektika publik sampai pada kalimat putus asa. Mana ada pemimpin tidak korupsi? Beliau hanya kena sialnya saja? Nanti juga lepas setelah potong remisi, grasi, asimilasi dll. Publik seperti kehilangan harapan dalam soal pemberantasan rasuah. Cara macam apa lagi yang dapat menekan kasus korupsi hingga ke titik nadir.
Korupsi memang tak muncul begitu saja. Akarnya bisa struktur _(by system),_ juga kultur _(by individual)._ Struktur berkenaan dengan seperangkat sistem yang dipercaya dapat di utak-atik untuk menghindari atau bahkan melindungi pelaku. China percaya soal ini, sebab itu dibentuk badan anti korupsi dengan kewenangan _superbody._ Hasilnya, koruptor ketakutan di awal, namun berangsur meningkat 90% hingga 2019 (Kompas.com, 2020).
Pendekatan struktural rupanya tak mencipta jera. Para pelaku mungkin berpikir, kadar sangsi dan profit korupsi masih jauh lebih menguntungkan. Jepang dan Korsel mengelola rasa malu individu sebagai pendekatan kultural _(shy approach)._ Hasilnya, peringkat korupsi Jepang dan Korsel berada di bawah 50 negara dari 180 negara hasil survei Tradingeconomics (2022).
Pendekatan struktural memberi ruang bagi negara untuk menghukum seberat-beratnya. Batasnya hak asasi manusia. Namun bukankah para koruptor telah melanggar hak asasi orang banyak ketimbang hak asasinya sendiri. Kata seorang filosof Itali, _berzina merusak diri sendiri, namun korupsi merusak orang banyak._ Dengan alasan itu negara mesti hadir. Rasa bersalah itu akhirnya ditanggung negara lewat pilihan hukuman penjara, gantung, tembak mati, setrum, denda dll.
Sebaliknya, pendekatan kultural menyediakan ruang masyarakat memberi _punishment_ bagi pelaku setinggi-tingginya. Jangan heran bila seorang pejabat di Jepang dan Korsel melakukan _harakiri_ sebagai tebusan rasa malu yang tak terkira. Bagi mereka, korupsi adalah aib besar yang tak hanya membunuh harga diri, juga martabat keluarga, bangsa dan negara. Hanya kematian sukarela yang bisa menebusnya. Nilai seseorang dianggap sepadan dengan kucuran darah dan kematian.
Lalu bagaimana mengatasi realitas korupsi di tengah semakin tingginya keserakahan atas nama kuasa. Dulu kita percaya bahwa lewat pendekatan struktural (sistem) dapat memaksa orang buruk menjadi baik. Tapi kini kita semakin sadar bahwa sistem memang penting, namun jauh lebih penting membangun pondasi manusianya (revolusi mental). Sebab selain kitab suci, bukankah manusia yang memproduk sistem itu sendiri. Senafas dengan pesan _founding fathers,_ bangunlah jiwanya baru kemudian raganya.
Disitu kita dapat memahami mengapa generasi di Asia Timur dan Eropa sejak kecil ditempa lewat kurikula afeksi seperti disiplin, antri naik bus, memungut apa saja yang bukan miliknya ke wadah anti korupsi. Semua itu adalah bentuk konkrit dari projek _zona integritas_ yang dimulai dari hal kecil, diri sendiri, dan dari sekarang. Tidak hanya itu, eskalasi korupsi dianalisis lewat pendekatan _Ishikawa (fishbone)._ Tujuannya menemu-kenali sebab masalah, ketaksesuaian dan kesenjangan utama.
Jika kita hanya berharap semata pada sistem, itu tidak keliru. Pendekatan sistem punya kelebihan yaitu menang dijumlah tangkapan, memperbanyak koruptor di buih, serta menyesakkan isi Lapas. Eksesnya negara kehabisan kocek memberi makan koruptor di tengah fakta bahwa mereka kenyang dan kaya, sementara negara semakin papa dan kerontang. Negara hanya menangkap, tapi gagal mencegah keserakahan merajalela.
Untuk menegakkan sistem sedemikian itu, kita rela menghadirkan pemimpin otoriter agar dengan paksaan fisik kesadaran dapat tumbuh dari perasaan terpaksa ke kesadaran alamiah. Ini tindakan revolusioner walau tak perlu berharap lebih seperti China. Kita bisa menyederhanakan sistem pemilu berbiaya tinggi kedalam mekanisme tak langsung, atau memutus keterikatan pejabat politik terpilih sebagai ketua Parpol. Ini semua dapat dilakukan lewat perubahan sistem, mekanisme maupun prosedur teknis politik.
Mendampingi itu kita butuh upaya kultural agar rasa malu pada diri, manusia dan Tuhan dapat dikembangkan. Bukankah kita mahluk religi yang dijejali doktrin anti mencuri (korupsi). Mengingat mayoritas penduduk beragama, semestinya kita dapat mempraktekkan nilainya dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Transformasi nilai kedalam tingkah laku adalah tanggungjawab institusi keluarga, organisasi pendidikan/masyarakat, dan pemerintah. Ketiganya wajib terlibat aktif sehingga korupsi tidak hanya urusan KPK, Polisi, Jaksa, dan ICW. Dia mesti menjadi gerakan aksi.
Religi penting dilibatkan agar tak nampak sekedar ritus belaka. Agar nilainya tak berjarak dari praktikal, semestinya dari sanalah kultur anti korupsi itu dibangun. Setidaknya manusia takut pada Tuhan, bukan pada penegak hukum. Dengan begitu religi hadir dalam rupa, dalam gerak, dalam laku, dan dalam tindakan nyata, bukan identitas semata. Jika tidak, religi akan terlihat garing, walau sesekali garang karena sentimen simboliknya. Gus Dur mengingatkan, membiarkan korupsi dengan sibuk oleh ritus sama saja membiarkan proses pemiskinan bangsa yang kian melaju.
Asa ini penting, sejauh kita masih percaya bahwa korupsi dapat diberantas dengan cara kultural disamping pendekatan struktural. Mungkin catatan Algernon Sidney perlu diingat, jika kejahatan dan korupsi merajalela, kebebasan tak akan bertahan. Sebaliknya, jika kebajikan terus diupayakan, kekuasaan sewenang-wenang tak bisa di bangun.







