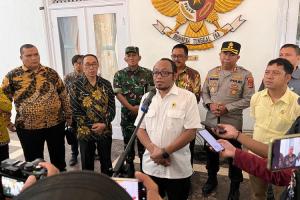Oleh: Yuri O. Thamrin
Pandemi covid-19 hingga saat ini masih menghantui dunia. Tantangan ke depan pun dirasakan sangat berat. Bukannya mereda, bayang-bayang "gelombang kedua" dari badai covid-19 justru mulai tampak di banyak negara pada akhir tahun 2020 ini.
Belum ada obat dan vaksin yang ampuh untuk virus covid-19. Tentunya, makin lama pandemi bersama kita, makin besar "biaya ekonomi dan penderitaan manusia" yang harus kita tanggung. Juga, beban psikologis terasa kian menghimpit masyarakat akibat rasa takut dan kuatir yang ditimbulkan virus covid-19.
Pada setiap kejadian tentu ada hikmah dibaliknya, termasuk pandemi covid-19 ini. Apakah pelajaran berharga yang dapat kita petik darinya? Tulisan ini akan mengulas beberapa pelajaran penting di balik wabah covid-19 itu.
DANA "CEKAK" UNTUK PENANGANAN PANDEMI
Sejatinya, pandemi covid-19 jauh lebih berbahaya dari pada ancaman terorisme. Hanya dalam tempo beberapa bulan, covid-19 (pada Agustus 2020) telah menginfeksi lebih dari 23 juta orang, mengakibatkan kematian lebih dari 800 ribu jiwa dan telah menimbulkan kerusakan ekonomi masif di banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun demikian, anggaran untuk menghadapi pandemi sangat kurang dibandingkan dana untuk memerangi terorisme (Foreign Affairs, Juli/Agustus 2020). Sebagai contoh, anggaran World Health Organization (WHO) pada 2018-2019 hanya US $ 4,4 milyar. Padahal, organisasi ini berperan vital untuk menangani berbagai penyakit dan ancaman pandemi terhadap dunia.
Sementara itu, anggaran riset dan pengembangan vaksin pun tidak memadai. Itulah sebabnya 17 tahun sejak merebaknya wabah SARS pada 2003 dan 8 tahun setelah terjadinya wabah MERS pada 2012, belum ada vaksin untuk kedua jenis virus itu. Sejatinya, virus SARS dan MERS masih "satu keluarga" dengan covid-19 --- yaitu sesama virus corona namun dengan strain yg berbeda.
Jika saja vaksin untuk virus SARS dan MERS sempat dikembangkan beberapa tahun yang lalu, maka akan tersedia pijakan (stepping stone) yang kokoh bagi upaya kita saat ini untuk memperoleh vaksin covid-19.
RENCANA DAN PERENCANAAN
Jenderal Eisenhower -- Presiden AS ke-34 dan pahlawan Perang Dunia II -- membedakan antara konsep "rencana" (plan) dan konsep "perencanaan" (planning).
Konsep "rencana" mengacu pada kondisi dimana pasukan, senjata, logistik dan hal-hal lain yg diperlukan telah tersedia dan dapat "digerakkan" ketika perang meletus (outbreak of war).
Sementara itu, konsep "perencanaan" mengacu pada berbagai bentuk persiapan pada masa damai (peace time) baik terkait pasukan, material, senjata (arsenal) dan hal-hal lainnya agar kesiapan perang yang kita miliki benar-benar maksimal pada waktunya.
Dengan kata lain, organisasi militer tidak akan menunggu "outbreak of war" untuk menyiapkan tank, pesawat, kapal induk dan lain-lain hal yg mereka perlukan. Ketika perang pecah, semua pelengkapan tersebut telah siap tersedia dan bisa digunakan secara efektif melawan musuh.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana halnya dengan kesiapan kita dalam "perang" menghadapi Covid-19 saat ini?
Sayangnya, kita tidak siap dan bahkan baru mulai "mencari" vaksin dan obat ketika wabah sudah merebak dan menelan jutaan korban.
Oleh karena itu, ke depan perlu ada strategi "guesstimate," yakni kemampuan untuk "mengantisipasi" dan "memprakirakan" jenis-jenis vaksin prioritas yang perlu dikembangkan agar dunia selamat dari ancaman pandemi di masa yang akan datang.
NEXT BIGGER PANDEMIC
Tentunya, kita semua berharap wabah covid-19 dapat segera diatasi dan kedepannya tidak ada lagi pandemi "berat" seperti itu. Namun, harapan dan realitas sering tak sejalan.
Banyak akhli justru memprakirakan bahwa umat manusia harus bersiap-siap untuk menyongsong pandemi atau krisis kesehatan yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, kemungkinan datangnya "era pasca antibiotik" sama sekali tidak boleh kita abaikan.
Dewasa ini, penggunaan antibiotik sangat berlebihan baik pada manusia maupun hewan (overuse of antibiotics). Akibatnya, banyak bakteri -- seperti pnemonia, tubercolosis dan gonorrhea -- makin resisten terhadap antibiotik.
Sejatinya, tantangan saat ini adalah bagaimana segera menemukan "antibiotik jenis baru yang lebih ampuh." Tanpa penemuan itu, kita bisa saja terjerembab ke dalam "era kegelapan" dimana nyawa kita dapat terancam karena antibiotik tidak lagi efektif terhadap berbagai bakteri. Sulit membayangkan bagaimana operasi dapat dilakukan dalam "post-antibiotics era" seperti itu.
Dalam 2 dasa warsa terakhir, umat manusia menghadapi beragam pandemi seperti wabah SARS (2003), MERS (2012), Ebola (2014-2016) dan Zica (2015-2016). Ke depan bukan tidak mungkin akan muncul jenis virus lain yang sangat berbahaya.
Apalagi jutaan manusia kini hidup berdekatan dengan unggas dan hewan dagangan mereka. Juga praktek industri peternakan yg tidak sehat dimana ribuan hewan berbagai jenis disatukan dalam tempat yang sama, sempit dan berhimpitan. Sementara itu, kebiasaan sebagian orang mengkonsumsi jenis-jenis hewan eksotis dan "tak lazim" pun dapat memicu transmisi virus hewan pada manusia.
Dalam pengembangan vaksin-vaksin strategis, "kehadiran" dan "peran" negara sangat diperlukan. Prof. Michael Osterholm (Foreign Affairs, Juli/Agustus 2020) mengingatkan bahwa industri farmasi sulit untuk melakukan tugas itu karena pengembangan vaksin strategis sangat mahal dan tidak memiliki nilai komersial yg instan. Dengan demikian, pendekatan pasar (market-driven approach) tampaknya sulit untuk mendorong pengembangan vaksin strategis dan karenanya peran negara dalam pendanaannya sangat diperlukan.
BEAUTY CONTEST
Dewasa ini, juga tampak adanya klaim terselubung (tacit claim) bahwa sistem otoriter cenderung lebih effektif dari pada sistim demokrasi dalam penanganan wabah covid-19. Tiongkok misalnya melancarkan "charm offensive" untuk mengkapitalisasi keberhasilannya menangani wabah covid-19.
Sementara itu, Amerika Serikat di bawah Presiden Trump tampak "babak-belur" menghadapi covid-19 dan saat ini AS adalah "juara dunia" dalam jumlah total infeksi dan jumlah total kematian akibat wabah ini.
Sejatinya, efektivitas penanganan wabah covid-19 tidak berhubungan dengan corak sistim politik. Walaupun Tiongkok relatif berhasil, namun banyak negara otoriter lain gagal melawan covid-19. Begitu pula, kegagalan AS tidak dapat digeneralisasikan sebagai kegagalan sistim demokrasi dalam penanganan covid-19, karena banyak negara demokrasi lainnya justru berhasil dan sangat impresif dalam mengelola wabah tersebut.
Apa pun corak sistim politiknya, ada 3 faktor yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan penanganan wabah covid-19, yakni (i) state capacities (ii) social trust dan (iii) leadership (lihat Francis Fukuyama dalam Foreign Affairs Juli/Agustus 2020).
Dalam konteks Amerika Serikat, negara Paman Sam ini selaku negara adidaya jelas memiliki "state capacities" yg sangat mumpuni. Namun, kapasitas itu tidak dapat dimaksimalkan karena masyarakat AS dewasa ini terpolarisasi dan kepemimpinan Presiden Trump pun problematik.
Presiden Trump misalnya bersikap "meremehkan" ketika diingatkan bahaya covid-19. Ia pun menolak untuk mengedukasi publik untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Di bawah Trump tidak ada upaya terpadu berbagai instansi pemerintah (government-wide efforts) untuk menanggulangi covid-19. Presiden justru melempar tanggung jawab kepada gubernur (negara bagian) dan kemudian malah menyalahkan pejabat daerah itu. Seharusnya sejak dini (sekitar awal Januari 2020), Trump perlu segera menyiapkan masker dalam jumlah cukup, ventilator, alat pelindung diri (APD), kapasitas testing serta strategi "contact tracing" yang handal.
Namun, semua itu tidak dilakukannya. Trump malah sibuk menyalahkan Tiongkok dan WHO sebagai "kambing hitam" dari kegagalannya sendiri mengelola pandemi covid-19 di AS.
Mengingat berlangsungnya Pemilu Presiden AS pada November 2020 ini, boleh jadi Trump akan membayar mahal untuk kegagalannya itu.
PERANAN INSTITUSI MULTILATERAL
Di tengah badai pandemi saat ini, berbagai lembaga multilateral dan organisasi internasional perlu memotori kerjasama internasional untuk memperkuat upaya kolektif memerangi covid-19. Sayangnya, harapan itu belum dapat terwujud secara efektif.
Berbagai lembaga internasional seperti G-7, G-20, DK PBB dan WHO justru terkesan lamban dan disfungsional. Sebagai contoh, G-7 tidak mampu menyepakati Final Communique-nya (Maret 2020) karena posisi AS yang memaksakan terminologi "Wuhan corona virus" pada dokumen tersebut. DK PBB (Maret 2020) juga tidak dapat membahas pandemi covid-19 karena penolakan delegasi Tiongkok. G-20 tidak dapat menyetujui usul IMF untuk menunda pembayaran hutang negara2 miskin selama wabah covid-19. Sementara, WHO pun lamban dalam mengumumkan "darurat pandemi" yang baru dilakukannya pada 30 Januari 2020 ---lebih sebulan dari saat covid-19 merebak di Wuhan pada Desember 2019.
Sesungguhnya, lembaga multilateral dan organisasi internasional hanyalah "platform" untuk menggalang kerjasama antar bangsa. Lembaga-lembaga itu tidak berhak membuat keputusan secara otonom dan hanya mencerminkan "kemauan politik," "aspirasi," dan "kesepakatan" dari seluruh negara anggotanya.
Dalam perspektif ini, "kelumpuhan" lembaga multilateral/organisasi internasional tersebut pada dasarnya bukan karena kesalahan lembaga-lembaga itu. Namun, lebih karena tensi yang tinggi di antara negara-negara anggotanya, terutama antara AS dan Tiongkok, sehingga proses multilateralisme menjadi "sulit," "repot" dan condong kurang produktif.
Akan halnya, "kelambanan" WHO mengumumkan "darurat pandemi," ada pemikiran untuk mengubah "spectrum of alerts" dari lembaga itu. Ke depan, tanda bahaya yang dikeluarkan WHO tidak lagi bernuansa "binary" (yakni "all or nothing") tetapi harus lebih bergradasi yakni: aman, waspada, siaga dan bahaya. Diharapkan, melalui tanda bahaya yang bergradasi itu, negara-negara anggota dapat mengambil langkah-langkah secara cepat, proporsional, cermat, terukur dan seksama guna penanggulangan pandemi.
Hal lain yang perlu pula dicermati adalah kecenderungan negara-negara kaya untuk memborong vaksin demi kebutuhan warganya sendiri. Kecenderungan ini nyata terjadi ketika dunia diterjang pandemi di masa-masa yang lalu. Oleh karena itu, ke depan WHO harus dapat mengembangkan Protokol guna menjamin akses bagi setiap negara untuk memperoleh vaksin.
KECENDERUNGAN DE-GLOBALISASI
Dewasa ini, banyak pengamat berbicara tentang terjadinya de-globalisasi akibat wabah covid-19. Terminologi de-globalisasi dalam konteks tulisan ini diartikan sebagai "pelambatan globalisasi" atau "perbaikan globalisasi" dan bukan peniadaannya.
Dilakukannya "lockdown" akibat wabah covid-19 praktis menghambat perjalanan non-esensial lintas batas negara, bahkan juga perjalanan di dalam negara. Dengan demikian, "lockdown" adalah bentuk "pelambatan globalisasi" yang kasat mata. Namun, terhambatnya keterhubungan fisik tersebut justru diimbangi dengan peningkatan globalisasi secara daring (on-line).
Dalam pengertian lain, banyak politisi menyoroti bahaya globalisasi dalam arti rantai pasok global (global supply chain) yang condong didominasi Tiongkok. Dalam konteks ini, ada ketakutan bahwa ketergantungan pada Tiongkok dapat "menyandera" kepentingan negara-negara industri lainnya.
Oleh karena itu, AS, Uni Eropa dan Jepang mencoba "memperbaiki globalisasi" dengan cara mendorong pengusaha-pengusaha mereka keluar dari Tiongkok dan merelokasi pabrik-pabrik mereka ke tempat lain.
Dalam perpektif ini, relokasi tersebut jelas menguntungkan negara-negara seperti Indonesia yang siap menyambut kedatangan para investor tersebut. Oleh karena itu, RI perlu meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi dan harus mampu bersaing dengan para kompetitornya.
***********